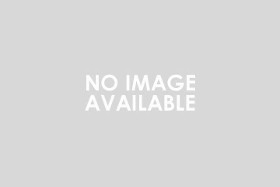Teks Diamond (2002) terkait dengan “rezim hibrida” atau “rezim gabungan” sangat sesuai untuk menjelaskan situasi politik Indonesia dalam dua periode kepemimpinan sebelumnya. Pendapat utamanya, seperti dikutip dari Carothers (2002), cukup simpel: tidak setiap negara yang melewati “gelombang ketiga” transisi demokratis pada tahun 1990-an berhasil menetapkan dirinya sebagai sebuah “demokrasi lengkap”. Beberapa bergerak stagnan bahkan cenderung menggunakan kombinasi sistem demokratik dan otoritarian secara bersamaan. Terdapat pula beberapa kasus dimana proses tersebut kembali merosot ke arah belakang.
Terdapat enam jenis sistem pemerintahan yang dikemukakan oleh Diamond menurut penulis ahli politik lainnya di artikel tersebut. Beberapa dari sistem-sistem ini meliputi: “demokrasi liberal, demokrasi elektoral, rezim ambiguitas, otoritarian bersaing, otoritarian dengan pemilihan dominan, serta otoritarian tertutup secara politis”.
Dengan bersandar pada penilaian
Freedom House
Pada tahun 2001, Diamond menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori “Rezim Samar” dengan peringkat indeks demokrasinya sebesar 3,4 pada skala yang berkisar dari 1 yang paling terbuka hingga 7 yang paling tertutup. Menurutnya saat itu, Indonesia berlokasi di area antara rezim “Kompetisi Otoriter” dan “Demokrasi Berbasis Pemilihan”.
“Kompetitif Otoriter” menggambarkan bahwa pemilihan umum berlangsung secara kompetitif namun tetap terdapat kendali serta manipulasi dari para petinggi. Sedangkan “Elektoral Demokrasi” menyiratkan bahwa hak-hak rakyat dalam hal kebebasan hanya bersifat prosedur saja, bukannya substansial.
- [Foto] Gambar Terpilih Minggu Ini, Aksi Demonstrasi Menentang UU TNI di Berbagai Wilayah
- Penggemar JKT48 Bergabung dalam Demonstrasi Melawan RUU Tentang TNI di Depan gedung DPR
- Usulan Perubahan Undang-Undang Tentang TNI Dipersepsikan Meneguhkan Kebijakan Militarisme di Area Publik serta Dunia Maya
“Rezim Tidak Jelas” terletak di tengah-tengah karena jejak-jejak otoriterisme masih bertahan dan pemilu belum memberikan kebebasan yang signifikan. Hambatan untuk mengekspresikan diri dengan aman serta ketidaktentuan ekonomi belum benar-benar lenyap. Maka pertanyaannya adalah: Apakah Indonesia saat ini tetap termasuk dalam kelompok “Rezim Tidak Jelas”, tanpa banyak perubahan?
Berdasarkan analisis dari catatan Diamond tersebut, meskipun ia telah menyebutkan beberapa ciri khasnya, situasinya sampai saat ini tetap stagnan. Otoritarianisme masih banyak diamini dan proses pemilihan umum hanya sebatas ritual kosong. Adegan politik dipenuhi oleh negosiasi antar elit penguasa tanpa ada penentangan nyata dalam lembaga legislatif. Berkali-kali suara publik ditolak begitu saja atau bahkan dimusuhi dan disensor. Apabila tren dominasi semacam itu terus berlanjut, kemajuan peralihan menuju demokrasi bisa-bisa meredup dan justru mengarah pada regresi. Mungkin bukan “Rezim Ambiguitas” yang kita hadapi melainkan berganti ke sistem “Kekuasaan Berkompetisi”.
Karena ciri khas dari sistem terdahulu masih melekat pada politik kita saat ini. Pemilihan umum hanya menjadi acara berkala sementara pemerintah sudah memperkokoh kedudukannya menggunakan instrumen negara. Sistem ini terus mencoba meredam lawan melalui ancaman dan tekanan hingga mereka benar-benar tidak berdaya. Ini termasuk potensi kekuatan warga yang bermunculan untuk menentangnya.
Secara singkat, menurut Diamond, pemilihan umum hanyalah topeng untuk mengelak dari “tekanan dalam negeri dan luar negeri”. Oleh karena itu, tidak heran apabila berbagai pihak mendeskripsikan “rezim campuran” tersebut sebagai ”
Pseudodemocracy
” atau “demokrasi palsu”.
Dari Kepolisian ke Tentara Nasional
Dalam dua periode kepemimpinan sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana “Rezim Abu-abu” ini bekerja secara terbuka. Ketika Prabowo memasukkan perwira aktif militer ke dalam kabinet, hal itu membawa kenangan akan era pemerintahan Jokowi dengan aparatur kepolisian di dalamnya. Dalam sebuah negara demokrasi liberal, TNI dan Polri merupakan badan defensif dan keamanan yang harus bersikap netral; campur tangan mereka dalam urusan politik bisa sangat merugikan.
Akan tetapi, kedua pihak malah mengekspos perangkat itu ke dalam cincin rejiminya. Memanfaatkan satuan-satuan tersebut untuk mencapai ambisinya secara politis. Sebenarnya, TNI-Polis tidak boleh diposisikan di lembaga-lembaga sipil saat mereka belum pensiun atau mengundurkan diri.
Partisipasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisan secara aktif dalam posisi sipil sangat riskan karena mereka tetap memiliki alat ‘pendam’ dan ‘kekerasan’, yang merupakan bagian integral dari fungsi mereka sebagai unsur pertahanan dan keselamatan nasional. Keistiman tersebut dapat dipakai untuk menekan kritikan terhadap para pejabat militer yang nantinya mungkin akan menduduki kedudukan sipil.
Selayaknya hukum menghalangi anggota TNI dan polisi dari aktivitas politik saat ini. Mereka tidak diberikan hak sufragium di dalam pemilihan umum sehingga dapat menekan potensi bias serta penyaluran sumber daya kedua lembaga itu demi tujuan-tujuan politik terbatas. Ini adalah dasar pikiran yang mendukung sistem pemerintahan sipil demokratis: agar keduanya tetap netral karena telah dilengkapi dengan senjata secara resmi oleh negara. Alat kekuatan milik mereka sangatlah riskan apabila digunakan oleh kelompok tertentu hanya untuk maksud-maksud politik belaka.
Ingkar Janji Reformasi
Dalam dua periode kepemimpinan terdahulu hingga kini, kita melihat pergeseran menuju sistem ‘polisi’ dan ‘militer’, di mana mereka mengejar optimalisasi efektivitas hierarki dalam rangka kemajuan dan industrialisasi. Tindakan-tindakan keras pun mulai ditampilkan. Kedua fase tersebut tidak menghormati janji reformasi. Mereka gagal mewujudkan visi dari suatu pemerintahan yang didasari oleh supremasi sipil.
good governance
Faktanya, hal itu sangat berbeda dengan kesannya. Sebaliknya, secara bertahap namun pasti, Indonesia mulai merosot menuju otoritarianisme. Terakhir, penghidupan kembali ‘Dwi Fungsi’ sudah dilegalkan. Kekhawatiran tentang kemungkinan bangkitnya Orde Baru lagi sekarang menjadi lebih nyata.
Perasaan itu telah terbayangkan dari waktu yang lama. Ini dimulai ketika banyak anggota kepolisian ikut serta dalam pemerintahan Jokowi. Selanjutnya adalah peran TNI dalam proyek nasional penting yang tidak berhasil, ”
food estate
“Ditindaklanjuti dengan pelaksanaan retret militer untuk para pejabat baru dan kepala wilayah. Kemudian, penugasan personel TNI aktif ke posisi sipil belakangan ini. Kesemuanya menjadi indikator dari adanya proses serupa militarifikasi dalam administrasi negara. Angkatan bersenjata, serta kepolisian, dilihat sebagai wujud nationalism dan patriotisme. Kedua institusi tersebut diyakin memiliki kemampuan lebih baik dalam mengatur masalah-masalah sipil lewat jaringan hierarki dan sikap ‘ руков
yes, man
” mereka terhadap pimpinan.
Supremasi Sipil versus Militer
Akan tetapi, terdapat dua hal penting yang kurang diperhatikan tentang supremasi militer atas sipil itu.
Pertama
Pelibatan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara langsung dalam lembaga-lembaga sipil dapat perlahan-lahan mengarahkan pemerintah menuju tirani serupa diktator militer. Ini karena kemungkinannya cukup besar bahwa dorongan kuasa ekstra ini tersebar luas antar banyak orang dari TNI. Kemudian, kesempatan bagi mereka memegang kendali atas semua aspek pemerintahan di waktu mendatang pun terbuka lebar. Selain itu, meletakkan anggota-anggota TNI pada posisi-posisi sipil tersebut memiliki potensi untuk menyebabkan konflik internal. Hal ini membuat individu-individu tersebut bersaing demi kedekatan dengan pusaran kekuasaan, sehingga merubah prajurit-prajurit menjadi sosok-sosok yang cenderung opportunistik dan praktis.
Lebih parah lagi, menyuarakan kritikan terhadap organisasi sipil yang dikendalikan oleh militer tak tertutup kemungkinan bakal ditanggapi dengan tindakan pengekangan menggunakan sumber daya militer yang tetap melekat pada tokoh pilihan tersebut. Hal itu sangat mengkhawatirkan, lantaran hingga saat ini umumnya dimengerti bahwa badan militer cenderung enggan dibebani pantauan publik secara maksimal. Akibatnya, ketidakefisienan dalam organisasi serta perilaku suap-menyuap dapat berlanjut tanpa kendali. Selain itu hal ini pun membawa risiko besar karena organisasi sipil yang dikuasai anggota militer aktif bisa jadi tempat potensial bagi pertentangan kepentingan sehingga memunculkan para otoritas baru dari kalangan militer. Korupsi yang semakin merajaleka akan setara dalam skala luas bahkan jika rezim disipliner digerakkan oleh tentaranya sendiri.
Kedua
Mempertanyakan kemampuan sipil dan militer di birokrasi dapat menghancurkan koherensi sosial yang telah lama menjadi fondasi kekuatan negara Indonesia dengan keragamannya. Penelapan atas hak-hak warga sipil serta penekanan pada privilese militer pastinya akan menimbulkan protes publik yang semakin kuat. Hal tersebut nantinya bakal mencetus ketidakstabilan politik panjang yang memiliki potensi untuk membawa dampak buruk kepada ekonomi negeri kita. Unjuk rasa masif dan mungkin bertambah parah setiap harinya merupakan sebuah ancaman signifikan terhadap legitimasi pemerintahan sekarang. Terlebih lagi, permasalahan utama seperti pemutusan hubungan kerja skala luas dan tantangan ekonomi lainnya belum sepenuhnya hilang dari pikiran publik.
Oleh karena itu, mengembalikan militernya ke barak sendiri serta mencabut UU TNI lewat PerppU adalah tindakan tepat untuk membawa pemerintahan lebih dekat pada tujuan reformasi. Saat ini, penting bagi mereka untuk mengetahui bahwa ‘ordo baru’ tak seharusnya dilihat sebagai contoh sukses dalam politik yang telah melepaskan Indonesia dari jeratan korupsi seperti yang kerap disuarakan. Justru hal tersebut jadi penggambaran gelap masa lampau negeri kita.